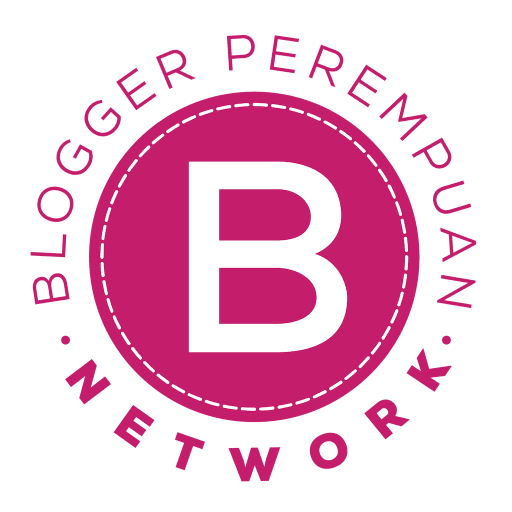Jika hatiku bisa berbicara kepada Allah hari ini, apa yang ingin ia sampaikan?
Aku ingin bilang,
Izinkan aku berdiri di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Dengan segala kerentanan dan ketakutan yang menyertainya. Aku menyadari bahwa seringkali aku melupakan-Mu di tengah hiruk pikuk urusan dunia yang tak ada habisnya. Namun Engkau tetap menjadi cahaya yang tidak pernah padam, bahkan di saat-saat kegelapan datang menyelimuti yang terasa begitu menyesakkan.
Ya Rabb, bimbing aku agar langkahku tidak tersesat dalam labirin kehidupan yang fana ini. Hadirkan cahaya-Mu agar aku dapat melihat jalan-Mu yang benar. Menghilangkan kabut yang memenuhi pikiran dan menjauhkanku dari jurang keputusasaan yang begitu gelap dan panjang.
Ingatkan aku, Ya Allah, bahwa hidup ini adalah ujian yang bersifat sementara. Bahwa setiap detik yang kulalui adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Dan akhirat adalah rumah yang kekal, tempat balasan sejati atas setiap usaha yang aku kerjakan dengan ikhlas.
Bimbing aku untuk menjadi hamba yang Engkau ridhai. Bukan manusia yang mengejar kepuasan dunia, melainkan jiwa yang tentram dalam naungan cinta dan kasih-Mu.
Ketika dunia menarik perhatianku ke arah yang salah, ingatkan aku bahwa Engkau adalah pusat dari segalanya. Ajarkan aku untuk menyucikan niat, agar setiap langkah yang aku ambil, setiap nafas yang aku hembuskan, semata-mata hanya untuk-Mu.
Ketika dunia sibuk memperjuangkan kekayaan dengan segala cara, hingga aku mulai mengeluh dan melupakan segala nikmat-Mu, ingatkan aku bahwa rezeki ku sudah Engkau atur dengan sempurna.
Ketika seluruh dunia mencari validasi dari sudut pandang manusia lain, ingatkan aku bahwa nilai diriku hanya berasal dari-Mu. Engkau adalah satu-satunya yang berhak menilai, bukan manusia fana yang juga mencari jawaban yang sama
Dan ketika hati mulai terbagi untuk mencintai urusan dunia yang sementara, ingatkan aku bahwa hatiku adalah milik-Mu semata. Seluruh aktifitasku, pengorbananku, sepenuhnya untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang-Mu.
Ya Rabb, ajarakan aku untuk terbebas dari belenggu penilaian duniawi yang kadang membutakan mata hati hingga melupakan kehadiran-Mu.
Ya Allah, The One my heart was created to seek, pull me away from every false worship, from anything that divines my devotion, until nothing fills my longing but You.
Ya Wahid, Unify my pursuit into a single direction. And when the world pull me apart, center me in Your oneness.
Ya Ahad, open my heart to see that nothing compare, so that I'm never overly impressed by anyone but You. And I come to love Your names and attributes in a way that fress me from all others but You.
Ya Witr, when I stand alone at the close of the night, let my solitude remind me of Your singular majesty. Make my heart distinct by its devotion, and make me one of Your servants. (Who Owns Your Heart? Allah's Name Ep.2 Dr. Omar Suleiman)
"Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim." (QS. Al-Anbiya: 87)
.png)